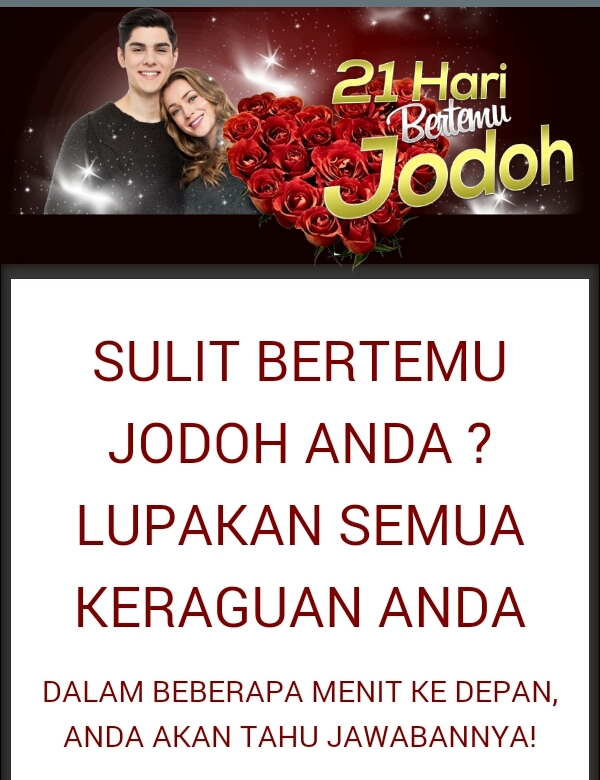MAHABHARATA
Oleh: A.S. Laksana
Buku Satu: Adi Parva
Dengan pikiran yang lumpuh oleh kepedihan, Santanu menjaga sumpahnya. Ia tidak pernah menanyakan, bahkan dalam saat-saat paling intim di antara mereka, kenapa Gangga membuang putra mereka ke sungai.
Setahun berikutnya Gangga hamil lagi, melahirkan lagi, pergi ke sungai lagi, dan membuang bayinya lagi. Santanu hanya bisa mematung menyaksikan semua itu. Ia terikat sumpah dan tak sanggup berkata apa pun ketika Gangga melingkarkan tangan ke lehernya setelah membuang bayi.
Tujuh kali Gangga melahirkan; tujuh kali Santanu menyaksikan perempuan itu membuang bayi yang dilahirkannya, dan sang raja menjadi semakin pendiam. Ia tetap menjalankan pemerintahan, tetapi dengan perasaan compang-camping dan luka tak tersembuhkan dan kabut yang memerangkap pikiran.
Siapa perempuan itu sebenarnya? Pada hari-hari lain di luar hari ketika ia pergi ke sungai membuang bayi, Gangga tidak bercela. Santanu melihat dalam diri perempuan itu segala bentuk kebajikan paling luhur: Tangan dan suaranya sama lembutnya dan matanya memancarkan belas kasih dan ia menyayangi kehidupan.
Setiap pagi Santanu akan mendengar perempuan itu menyanyi. Gangga selalu menyambut kehidupan dengan doa dan nyanyian suci; ia menyayangi orang-orang di sekitarnya, rusa di taman, dan serangga-serangga. O, bagaimana kelembutan semacam itu sanggup melakukan kejahatan yang tak pernah terpikirkan oleh siapa pun? Ia welas asih kepada semut-semut, tidak membunuh nyamuk, tetapi tujuh kali membunuh bayi-bayinya sendiri.
Santanu merasakan pikirannya kian gelap; ia terperosok ke tempat terburuk dan tak sanggup melakukan apa pun untuk bangkit dari tempat itu. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak sanggup membenci Gangga.
*
Pagi itu seorang menteri tua, orang yang ia percaya, menanyakan ke mana para pangeran yang dilahirkan oleh permaisuri. Santanu menjawab bahwa putra-putranya lahir dengan penyakit yang disebabkan oleh kutukan purba dan mereka harus diserahkan perawatannya kepada seorang resi di tempat tersembunyi.
Itu kebohongan yang membuat dadanya sesak saat menyampaikannya. Demi menghindari pertanyaan yang memaksanya berbohong, ia menjauhi semua orang, termasuk para sesepuh yang paling setia kepadanya.
Ia ingin menjauh juga dari Gangga, tetapi tidak bisa. Ia tetap tidak sanggup menjauhinya meskipun ia kadang meyakini bahwa istrinya adalah raksasi, makhluk jahat yang dikirimkan oleh kegelapan untuk menghancurkannya, melemahkan akalnya, memberinya penderitaan yang tak akan pernah tersembuhkan. Yang paling menyakitkan baginya adalah perempuan itu tidak terlihat menyesali tindakan kejinya membuang tujuh bayi yang dilahirkannya.
“Saya mewakili semua orang yang menyayangi anda, Tuanku. Di manakah gerangan putra-putra Tuanku saat ini?”
Pertanyaan itu, yang disampaikan menteri tua pagi tadi, membuat Santanu rusuh hingga larut malam. Ia harus melakukan sesuatu kepada raksasi itu, tapi apa? Di puncak kegelisahannya malam itu, ia mendengar suara lembut Gangga dari kamarnya. Perempuan itu menyanyikan doa tengah malam.
Santanu mendekatinya, Gangga menyambutnya, dan raja yang terluka itu membenamkan diri ke rambut hitam yang seperti arus sungai. Dan pada awal musim semi, Gangga hamil lagi dan sembilan bulan kemudian, pada malam menjelang kelahiran, Santanu menyelinap mendekati ruang persalinan. Semalaman ia berjaga di tempat tersembunyi dan pada dinihari ia mendengar tangis Gangga saat berjuang keras melahirkan bayinya; lalu tangis bayi; lalu nyanyian suci.
Ia hanyut mendengarkan nyanyian Gangga, tetapi segera sadar apa yang harus dilakukannya. Menjelang fajar, Santanu berangkat ke tepi sungai mendahului Gangga dan tiba di sana sebelum matahari dan memilih tempat tersembunyi untuk menunggu istrinya tiba di tempat ia biasa membuang bayi.
Waktu berjalan sangat lambat. Ia gelisah di tempat persembunyiannya.
Ketika matahari merah muncul di langit timur, kereta Gangga tiba di tepi sungai. Perempuan itu turun menggendong bayinya dan berdiri di tepi air menyanyikan mantra. “Hentikan!” teriak Santanu. Ia melompat dari tempat persembunyiannya ketika Gangga mengangkat bayinya tinggi-tinggi di atas kepala.
“Tidak akan kubiarkan kau membunuh anakku kali ini.”
Santanu berlari ke arah istrinya dan sebelum ia berhasil merebut bayi itu, Gangga sendiri mengulurkan bayi di kepadanya. Cepat-cepat ia menerima bayi itu dan mendekapnya kuat-kuat seperti mendekap hidupnya sendiri.
“O, malapetaka. Bagaimana mungkin seorang ibu tega membunuh bayi-bayinya sendiri?”
Gangga memandangi suaminya.
“Kau melanggar sumpahmu kepadaku,” katanya. Suaranya terdengar sedih. “Tampaknya kau lebih memilih putramu ketimbang aku. Baiklah. Dengan begitu, kutukan berakhir hari ini.”
“Kutukan? Bukankah kau sendiri kutukan itu, wanita pembunuh?”
Seperti anak panah yang paling mematikan, amarah di dalam kata-kata Santanu melesat menembus jantung perempuan itu. Dilihatnya mata Gangga meredup, dan berair, dan Santanu masih ingin melukainya enam kali lagi untuk membalas tujuh kejahatan yang telah dilakukannya sejak perempuan itu melahirkan bayi pertama.
Gangga mendekat, seperti kesedihan yang merayap pelan-pelan, lalu mengulurkan tangannnya. Santanu merasakan hatinya tercabik-cabik ketika jari-jari lembut perempuan itu menyentuh pipinya.
“Lihat aku, Santanu,” katanya.
Santanu memandangi istrinya dan melihat perempuan itu mengubah diri menjadi cahaya lembut dan gelombang kristal sekaligus: Ia lebih suci ketimbang udara pagi dan lebih terang daripada matahari.
“Aku Gangga, Santanu, sungai langit dan di bumi. Di dalam arusku manusia membasuh dosa-dosa mereka.”
Santanu beku dan sunyi, seperti tugu batu, tetapi di dalam dirinya ada arus bergulung-gulung, riuh dan membingungkan. Ia ingin berlutut menyembah perempuan di hadapannya, namun bayi di dalam pelukannya, yang hampir mati ditelan arus, dan tahun-tahun kepedihan membuatnya tak melakukan apa-apa.
Dan Gangga mengubah diri ke wujud manusianya, menuturkan dengan suara lembutnya tentang dua kutukan.
“Kutukan pertama menyebabkan aku datang kepadamu sebagai manusia, sebagai perempuan di tepi sungai, sebagai istrimu. Dulu, pada kehidupan lalu yang sudah hilang dari ingatanmu, karena kamu manusia yang terikat pada tubuh fanamu, kamu adalah raja dan namamu Mahabhiseka.”
Samar-samar Santanu teringat sesuatu, yang terasa olehnya seperti mimpi. Mahabhiseka duduk di dalam perjamuan dengan para dewa di Indraloka. Ia manusia, tetapi karena keluhuran dan samadinya, dewa memberinya keleluasaan untuk bertandang ke langit kapan saja ia ingin mengunjungi para dewa.
Dewi Gangga melintas di perjamuan itu dan angin bertiup menyingkap kainnya. Para dewa menunduk, Mahabhiseka tidak. Ia terpesona melihat Gangga, dan Gangga membalas pandangannya, dan ia juga terpesona pada Mahabhiseka. Hanya sesaat mereka bertatapan, tetapi para dewa melihatnya, dan itu terlarang di Indraloka: saling memandang dengan dada menyimpan hasrat, di dalam perjamuan para dewa.
Dewa Indra kemudian mengeluarkan kutukannya. Mahabhiseka akan tetap menjadi raja, tetapi tidak bisa lagi naik ke langit, dan Gangga akan menjalani kehidupannya sebagai manusia di bumi. Mereka akan menjadi suami istri, saling mencintai, dan merasakan kebahagiaan dan penderitaan karena cinta mereka.
“Itu sebabnya aku datang ke dalam mimpimu, Santanu, dan hadir di hadapanmu di tepi sungaiku.”
Santanu, Mahabhiseka pada kehidupan sebelumnya, merasakan kepedihan yang lain. “Sekarang kau akan meninggalkan aku?”
“Bukan aku yang menyebabkan perpisahan.”
*
Santanu merasakan bayang-bayang takdir yang tak terelakkan. Perpisahan. Lalu, dengan suara lemah, ia menanyakan: “Dan anak-anak kita? Kutukan apakah yang harus mereka jalani?”
“Mereka para wasu. Mereka membuat Resi Wasista marah dan mengutuk mereka.”
Wasu adalah dewa penghuni langit juga. Pada waktu itu, delapan wasu berjalan-jalan bersama para istri mereka, dan mereka melihat Nandini, lembu betina, yang sedang merumput bersama anaknya di lereng gunung tempat tinggal Resi Wasista.
Ketika mereka pulang ke langit dari jalan-jalan, salah satu istri wasu menginginkan Nandini dan ia merengek kepada suaminya.
“Untuk apa, Istriku?” tanya Prabhasa. “Kita tidak memerlukan susu Nandini agar hidup abadi. Kita sudah abadi.”
“Itu bukan untukku,” kata istrinya. “Aku menyayangi kawanku, seorang manusia, dan aku ingin ia hidup abadi.”
Prabhasa menggeleng. “Kita akan membuat marah Resi Wasista jika melakukannya.”
“Kalau kau takut pada Wasista, yang hanya manusia biasa, aku tak akan memaksamu menjadi pemberani.”
Dicemooh seperti itu, Prabhasa akhirnya turun bersama tujuh wasu lainnya. Mereka melesat dari langit seperti bintang berekor, melarikan Nandini dan anaknya.
Wasista tekun bersamadi dan baginya Nandini seperti putrinya sendiri. Ketika Nandini dan anaknya hilang, ia bisa mendengar rintihan lembu itu dan lolong ketakutan anaknya. Dan ia resi sakti. Ia tahu siapa yang telah mencuri lembu-lembu kesayangannya.
Dengan amarah yang tak tertahankan, ia memusatkan pikiran dan kemudian mengutuk para wasu: “O, dewa-dewa rendahan. Jadilah kalian manusia fana.”
Di langit, para wasu bisa merasakan kutukan itu. Betapa mengerikan. Mereka makhluk cahaya. Tak sanggup mereka membayangkan diri menjadi manusia, memiliki darah dan daging, dan hidup di bumi, dan mati, dan membusuk setelah mati. Mereka turun menemui Resi Wasista, mengembalikan Nandini dan anaknya, dan memohon pengampunan.
Wasista iba melihat para wasu itu dan bersedia memaafkan mereka, tetapi kutukan resi bukan sesuatu yang bisa ditarik lagi setelah diucapkan. “Aku hanya bisa melunakkannya,” kata sang Resi. “Tujuh dari kalian akan menjalani kutukan singkat. Kalian hanya akan menghabiskan sembilan bulan di kegelapan rahim ibu. Lalu kalian akan mati begitu dilahirkan. Dengan jalan itulah kalian kembali ke langit.”
Kepada Prabhasa, yang telah menyeret ketujuh wasu lain ke dalam dosa, Wasista berkata lembut: “Kamu harus menjalani hukumanmu secara penuh di bumi, Prabhasa, tetapi penyesalanmu dan restuku akan membawamu pada kehidupan yang luar biasa di bumi. Sekarang, kalian harus menemukan perempuan yang akan menjadi ibu kalian. Melalui rahimnya, kalian akan terbebas dari kutukan.”
Setelah itu Wasista membawa Nandini dan anaknya meninggalkan mereka. Ia harus bertapa untuk memulihkan tenaganya; bagaimanapun, mengeluarkan kutukan dan melunakkannya kembali telah membuatnya terkuras.
*
Dari teras padepokan yang ditinggalkan oleh Wasista, para wasu yang menanggung kutukan itu melihat mata air yang berkilau di bawah matahari. Dari sanalah Gangga bermula. Prabhasa mengusulkan mereka datang ke mata air itu dan memohon kepada Gangga. “Tidak ada ibu lain yang lebih baik bagi kita selain sungai yang mengaliri langit dan bumi,” katanya.
Mereka berangkat ke mata air dan terus memohon sampai Gangga muncul di hadapan mereka dan mereka berlutut di kakinya seperti delapan kanak-kanak meminta belas kasih ibu mereka. Prabhasa, dengan perasaan bersalah kepada teman-temannya, mewakili mereka:
“Dewi, jadilah manusia dan menikahlah dengan raja di bumi. Jadilah ibu bagi kami. Buanglah kami di sungaimu begitu kami lahir, agar terbasuh kami dari dosa-dosa, dan kami suci untuk pulang ke langit.”
Gangga mengabulkan permintaan mereka. Delapan wasu mengucapkan terima kasih dan kemudian melakukan samadi di sebuah gua di lereng gunung itu dan menghilang.
*
“Dengan aku sendiri menjalani kutukan, Santanu, dan selalu merindukan pertemuan denganmu, bagaimana mungkin aku menolak permintaan mereka?”
Sekarang, dengan pikiran jernih, Santanu berlutut dan meminta maaf kepada Gangga bahwa ia telah meragukannya dan menyebutnya wanita pembunuh. Lalu, tanpa bicara, ia serahkan bayi yang ia gendong kepada ibunya, dan Gangga, dengan gerak lembut yang membuat Santanu menyesali dirinya, menyambut bayi itu, Wasu Prabhasa, dari tangannya.
“Pulanglah ke Hastina,” kata Santanu.
“Aku pulang ke tempatku,” kata Gangga.
“Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi, Gangga? Aku akan datang ke tepian ini. Maukah kau menemuiku tanpa dilihat oleh manusia atau dewa?”
“Waktu kita bersama sudah berakhir, Santanu. Aku akan merawat putra kita. Nanti, pada hari ia berusia enam belas, aku akan membawanya ke tempat ini. Ia akan pulang bersamamu ke Hastina. Dan, ketika waktunya tiba, ia akan memerintah Kuru.”
Dengan mendekap bayi di dadanya, Gangga menghilang. Tangis Santanu menggema di langit, menggugurkan dedaunan di hutan, mengacaukan arus sungai. Berulang-ulang ia memanggil “Gangga! Gangga!” tetapi apa yang sudah berakhir tak bisa dimulai lagi dan arus Gangga tak pernah berbalik menuju hulu.[]